“The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.” -Robert Maynard Hultchins.
Semenjak merebaknya Covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan dan standar operasional prosedural (SOP) yang ketat di ruang publik demi keselamatan masyarakat. Termasuk di dalamnya mengalihkan proses pembelajaran di semua jenjang satuan pendidikan ke rumah. Tersebutkanlah hal itu dengan istilah pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah.
Dalam semester ini, fenomena tarik-ulur kebijakan pembelajaran jarak jauh itu menjadi salah satu realitas kehidupan sosial yang tidak dapat dihindarkan sama sekali. Utamanya, proses tarik-ulur kebijakan itu hampir mirip dengan gaya kamuflase bunglon yang membuat jengkel banyak pihak yang bersangkutan.
Pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara teoritis awalnya dipersepsikan sebagai angin segar yang menjanjikan keefektifan dalam kelangsungan pembelajaran. Namun dalam prakteknya, PJJ tersebut justru memberikan tekanan (red; persoalan) baru yang berlapis.
Tekanan demi tekanan baru yang berlapis tersebut di antaranya; mengharuskan orangtua mencurahkan perhatian penuh demi kelangsungan belajar anak-anaknya, memiliki dan menguasai gadget, menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok hingga tekanan psikis yang harus dijadikan kawan terbaik sepermainan di waktu yang tak terhingga.
| Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19 Antara Objektivitas dan Rekonstruksi Behavior |
Mendidik dan Mendampingi Belajar Anak Apakah Kewajiban Seorang Ibu?
Pengalihan ruang pembelajaran vis a vis (metode klasikal) menjadi ruang virtual pada kenyataannya mengoyak kembali kemapanan tatanan peran guru dan orangtua terkait efektivitas pembelajaran anak didik.
Dalam konteks pengalihan ruang pembelajaran inilah sejatinya guru sedang menyerahkan marwah untuk menjaga dan melestarikan lima aspek yang membentuk anak didik: dimensi intelektual, dimensi kultural, dimensi nilai-nilai transendental, dimensi keterampilan fisik/jasmani dan dimensi kepribadian manusia itu sendiri pada genggaman orangtua (Saiful Mustofa, 2017: x).
Jika selama ini pembelajaran teoritis dan moral secara porposional lebih terpusat dilakukan di sekolah dengan banyak melibatkan peran aktif guru maka pada pembelajaran jarak jauh adalah kebalikannya, di mana upaya itu lebih dominan mengandalkan peran orangtua.
Orangtua dan anggota keluarga yang ada di lingkungan rumah, kini tidak lain berperan sebagai pusat pembelajaran setiap masing-masing anak didik. Entah itu dalam mengerjakan tugas sekolah via daring atau pun upaya pembelajaran karakter kepribadian yang langsung dipraktekkan dalam kesehariannya.
Keadaan inilah yang kemudian disebut oleh Miss Thompson (seorang guru sekolah dasar) bahwa mengajar seharusnya banyak menyoal tentang to teach is to touch your student’s life. Mengajar bukanlah soal ego seorang guru melainkan soal anak-anak, semua murid kita (Saiful Mustofa, 2017: 53).
Penegasan itu menyadarkan kita bahwa dalam proses belajar bukan sekadar menyampaikan nilai (transfer of values) atau menyampaikan pengetahuan (transfer of knowledge) akan tetapi juga mengantarkan pada upaya menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru dari realitas yang ada di sekeliling anak didik (Nur Sayyid Santoso Kristeva: 2009).
Alhasil, orangtua dalam konteks ini harus pandai-pandai memanajemen waktu, antara menunaikan kewajiban dan tugasnya. Alih-alih berpindah tangan menjadi tanggung jawab kedua orangtua akan tetapi beban itu justru tampil lebih dikerucutkan pada sosok ibu.
Mengapa demikian? Apakah karena ada dalil yang menegaskan bahwa ibu adalah sekolah pertama? Atau memang itu terjadi karena orang yang berkutat dalam urusan domestik adalah seorang ibu? Atau mungkin karakteristik seorang istri idaman adalah sosok yang piawai dalam mendidik anak-anaknya.
Tentu dalam ‘pengerucutan’ beban itu akan ada banyak sudut pandang yang mengitarinya. Akan ada endapan alasan yang berlapis-lapis untuk mengatakan bahwa tugas mendidik anak adalah kewajiban seorang ibu, sementara seorang ayah akan sibuk mengais rezeki.
Sudah barang tentu, pola pikir dan habitus itu sudah telanjur mengerak di banyak kepala. Konstruksi sosial yang sangat pelik keadaannya. Terlebih lagi jika kita menanggapinya dengan argumentasi yang disandarkan pada sejubel teori dan alasan kreatif sebagai solutif pun belum tentu mampu diterima.
Bukankah kita dan orang-orang lebih suka berdiam diri di zona nyaman (red; konstruksi sosial patriarkal) daripada harus menerobos ocehan tetangga? Lebih takut tidak menuruti kemauan keras keumuman yang berlaku dalam ruang lingkup kehidupan sosial yang telah membudaya daripada merangkai hidup dalam pijakan kaki sendiri yang penuh lika-liku namun itu mematangkan konsep hidup kita.
Nampaknya benar apa yang dipersepsikan oleh Jakob Sumardjo (pelopor kajian filsafat Indonesia dan pemerhati sastra); tetapi, kalau kita ditakdirkan untuk lahir dan tinggal di suatu lokal di planet ini, mungkinkah kita menghindar dari tata nilai yang dilahirkan oleh masyarakat lokal itu?
Atas dasar itu pula, ada baiknya di sini harus ditekankan kembali bahwa konteks peran penting kedua orangtua dalam persoalan mendidik putra-putrinya adalah hal yang utama. Dalam pandangan Islam, peran seorang suami sejatinya meliputi segala-galanya. Mengurusi urusan domestik dan ruang publik. Sementara istri disebutkan hanya bertugas melayani suami semata.
Namun, mengapa yang terjadi dalam prakteknya justru sebaliknya? Seakan-akan, tugas dan tanggung jawab seorang istri lebih menggunung daripada seorang suami yang telah disebutkan dan persepsikan akut berperan sebagai imam. Bahkan konsep itu telah “mengakar dalam” sebagai cara pandang dalam memosisikan seorang lelaki yang belum menikah sekalipun.
Tidak percaya? coba saja buat riset kecil-kecilan tentang bagaimana cara pandang para perempuan tatkala mendefinisikan seorang lelaki lajang di luar sana. Tapi saya pikir, tidak menutup kemungkinan akan ditemukan pula cara pandang baru dalam pendefinisian konsep tentang sepak terjang laki-laki. Pasalnya, sejauh ini di mana-mana gerakan emansipasi dan aktivis kesetaraan gender yang kerap kali disebutkan dengan feminis telah lama menjamur.
Satu upaya menetralisir toxic masculinity dan relationship yang telah lama mendarah daging, meskipun dalam proses terjadinya sangat begitu alot. Aktivis feminisme itu berkoar di mana-mana namun pelecehan, stereotip, opresi dan eksploitasi terhadap perempuan jumlahnya tidak spontanitas surut.
Hal itu, tidak lain adalah bentuk sorak jelmaan yang menunjukkan bahwa khalayak orang masih alergi dengan hal-hal yang bertentangan dengan tradisi yang membudaya.
Mungkin, di sini kita bisa menangkap kunci permasalahannya, bahwa dalam parenting yang ideal mendidik dan mendampingi seorang anak belajar tidak melulu dijadikan sebagai beban ganda seorang ibu melainkan tugas dan tanggung jawab kedua orangtua, ibu dan ayah. Kedua orangtua sejatinya memiliki bagian dan porsi yang sama dalam membentuk kepribadian, karakter dan pengetahuan sang anak.
Sementara apa jadinya jika semua urusan domestik, ruang publik dan mendidik seorang anak dilimpahkan utuh kepada seorang ibu semata, lantas kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa jadi sikap infantil dan katarsis menjadi kontruksi kokoh dalam kepribadian anaknya.
Perempuan dan Mitos Mothering
Menyoroti persoalan tersebut, Alison Jaggar seorang tokoh feminis radikal-libertarian sibuk mempertanyakan kembali posisi sentral perempuan dalam mengasuh anak. Apakah mengasuh anak itu semata-mata termasuk sebagai mothering secara biologis atau mothering secara sosial?
Alison berpandangan, secara general mothering sejatinya mengacu kepada hubungan apa pun yang di dalamnya individu merawat dan menyayangi yang lain, maka seseorang tidak perlu menjadi seorang ibu biologis untuk menjadi ibu sosial, (Rosemarie Putnam Tong, 2010: 119).
Upaya Alison tersebut disambut baik oleh Ann Oakley dengan menegaskan bahwa motherhood biologis tak lain adalah mitos yang berlandaskan pada trilogi keyakinan kontruksi budaya; semua perempuan perlu menjadi ibu, semua ibu memerlukan anak-anaknya dan semua anak memerlukan ibunya.
Menurut Oakley, pertama, para perempuan sejatinya telah terdikte oleh konstruksi sosial patriarkal sejak dini untuk bermimpi menjadi sosok ibu. Pada kenyataannya hal itu mendapat dukungan kuat dari teori psikoanalisis populer dan pseduo saintifik.
Proses kerja sosialisasi tersebut yakni melalui habitus yang diterapkan di lembaga pendidikan, tempat ibadah (doktrin agama), segala bentuk media, lingkungan bermain, dan upaya yang dilakukan oleh psikiater, psikolog dan dokter dalam konteks memvonis kasus perempuan abnormal (maskulin dan enggan menjadi seorang ibu) untuk menjadi perempuan normal (feminim dan bercita-cita menjadi seorang ibu).
Jika perempuan tidak melalui proses panjang pembentukan itu maka perempuan tidak akan tumbuh-kembang menjadi perempuan yang perlu menjadi sosok ibu sekadar untuk mendapatkan penghargaan terhadap diri pribadi.
Lebih lanjut, Oakley menggarisbawahi bahwa kebutuhan yang “seharusnya” dirasakan oleh perempuan untuk menjadi seorang ibu sebenarnya “tidak ada hubungannya” dengan “kepemilikan ovari dan rahim” di dalam seorang perempuan, justru realitas yang terjadi sesungguhnya adalah tentang bagaimana cara perempuan dikondisikan secara sosial dan kultural untuk bercita-cita menjadi seorang ibu.
Kedua, keyakinan ibu memerlukan anak-anaknya tidak lain hanya akan timbul mana kala “insting keibuan” telah meliputi diri seorang perempuan secara utuh dan total, sehingga perempuan akan mengalami frustasi tingkat tinggi.
Sementara dalam pandangan Oakley, apa yang disebut insting keibuan sebenarnya tidak ada. Perempuan normal tidak mengalami hasrat untuk mempunyai anak biologis, dan dorongan hormonal (laiknya ngengat yang mendekati api di daerah tropis) baik itu selama dan setelah masa kehamilan.
Dalam hal ini Oakley hendak menegaskan bahwa insting keibuan pada dasarnya adalah dipelajari, bukan given. Hal itu dibuktikan dengan tidak sedikit dari perempuan yang pertama kali memiliki seorang anak tidak mesti disertai dengan pengetahuan akan fungsi ibu yang benar-benar memadai; entah itu tahu cara menyusui, menggendong, memandikan, merawat bayi dengan benar dan lain sebagainya.
Semua itu hanya akan mampu dilakukan tatkala ia melihat langsung, mempelajari dan dinasehati oleh perempuan yang telah menjadi ibu. Atas dasar demikian, ringkasnya, ibu itu tidak dilahirkan melainkan dibuat (dibentuk).
Ketiga, persepsi anak-anak memerlukan ibunya tak ayal adalah fitur paling opresif dari mitos motherhood biologis. Menurut Oakley, persepsi tersebut mengandung tiga asumsi lemah yang mengikat perempuan kepada anak-anaknya; pertama, kebutuhan anak terhadap sosok ibu paling baik dipenuhi oleh ibu biologisnya.
Kedua, seorang anak (utamanya yang masih kecil) membutuhkan perawatan yang kompleks dari ibu biologisnya, dibandingkan dengan perawatan dari ayah biologisnya atau pun orang lain.
Sementara yang ketiga, anak-anak pada umumnya hanya membutuhkan satu pengasuh untuk merawat mereka (lebih disukai ibu biologisnya).
Dalam pandangan Oakley ketiga asumsi yang mendukung pendapat anak-anak memerlukan ibunya tersebut adalah keliru. Pertama, ibu sosial sama efektifnya dengan ibu biologis. Hal itu dibuktikan bahwa perkembangan anak yang diadopsi memiliki kemampuan penyesuaian yang baik sama halnya dengan anak-anak yang dirawat oleh ibu biologisnya. Kedua, anak-anak tidak membutuhkan ibu biologisnya lebih daripada mereka membutuhkan ayah biologisnya.
Bahkan lebih dari itu, anak-anak bukan hanya tidak perlu dibesarkan oleh orangtua biologisnya, mereka juga tidak perlu dibesarkan oleh seorang perempuan.
Yang anak-anak butuhkan justru orang dewasa yang mau konsisten untuk menjalin hubungan dekat, yang dapat dipercaya, dapat dijadikan sebagai tempat bergantung, yang bersedia konsisten dalam melakukan perawatan, mendisiplinkan, mengakui dan senantiasa menerima-merayakan setiap keunikan yang dimiliki seorang anak serta selalu ada tatkala anak membutuhkannya. (Rosemarie Putnam Tong, 2010: 121)
Pada akhirnya, masing-masing kita bisa membuat simpulan mandiri bahwa laki-laki pun tidak kurang dari perempuan dalam upaya memainkan peran penting dalam tumbuh-kembang dan proses pendidikan seorang anak. Akan tetapi, pendidikan collective mothering atau sosialisasi kolektif (ibu dan ayah) terhadap satu anak lebih baik daripada pendidikan satu anak oleh satu orangtua secara eksklusif.
Sebagai contohnya, adalah anak-anak yang dibesarkan di Kibbutzim di Israel, di sana anak-anak secara merata mereka sama-sama bahagia, ceria, matang secara emosi, cerdas dan nyaman secara sosial. Berbeda halnya dengan anak-anak yang dibesarkan di bawah pendidikan satu orangtua yang eksklusif, seperti halnya di negara-negara yang melanggengkan budaya patriarkal.
| Baca juga: Fatima Mernisi Bukti Keberanian Pemikir Perempuan |
Kepemilikan dan kapabilitas atas gadget
Pembelajaran jarak jauh pada kenyataannya mengharuskan setiap kepala keluarga memiliki dan menguasai betul atas smartphone, tablet dan laptop.
Kehadiran piranti-piranti kemutakhiran teknologi ini yang semula dipandang dan diposisikan sebagai kebutuhan sekunder bahkan tersier oleh khalayak ramai namun kini beranjak cepat menjadi salah satu kebutuhan primer di berbagai lapisan sosial masyarakat yang ada.
Disadari ataupun tidak, dengan diberlakukan PJJ intensitas transaksi jual-beli gadget meroket tajam. Entah itu produk gadget yang benar-benar berkapasitas terupdate ataupun second (bekas) sekalipun penjualannya lebih laris di pasaran. Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 di satu sisi memberikan keberkahan bagi sebagian orang.
Tentu dalam prakteknya tidak hanya cukup sekadar memiliki gadget, akan tetapi orangtua dan sang anak juga harus menguasai betul cara penggunaannya. Mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi ruang belajar seperti WhatsApp, ruang guru, google class, google room, zoom, google meet, duo dan lain sebagainya.
Penguasaan atas gadget ini sangat penting untuk menunjang kelangsungan belajar dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimanapun proses pembelajaran jarak jauh ini akan banyak mengandalkan fungsi dari media pembelajaran. Sehingga sangat disayangkan, manakala proses panjang pembelajaran harus tersendat, tertunda dan terabaikan karena alasan ketidakmampuan mengopresikan gadget.
Namun fenomena kurang update dan ketidakmampuan atas gadget ini ada kemungkinan dari waktu ke waktu telah lama berangsur membaik.
Hal ini dapat kita lihat dari seberapa besar keaktifan khalayak ramai dalam membuat status di sosial media. Anak-anak, remaja, dewasa dan tua bahkan lansia lebih gemar menumpahkan kegelisahan hidupnya di jagat maya daripada memelihara budaya cangkrukan bersama di dunia nyata.
Sebagai dampak negatif dari penggunaan gadget yang laten, ruang lingkup realitas kehidupan sosial lebih terdikotomi dan terdistorsi secara masif. Merebaknya kasus kecanduan gadget, kekerasan dan kriminalitas meningkat.
Sebagai contohnya, mungkin kita masih ingat dengan maraknya pemberitaan media tentang membludaknya jumlah pasien yang kecanduan gadget di tahun 2019. Bahkan disebutkan per 15 Oktober 2019, terdapat 209 pasien dirawat di rumah sakit jiwa Cisaura Kabupaten Bandung Barat (sumber: wartakota.tribunnews.com)
Belum lagi ditambah dengan kekerasan verbal, fisik dan mental yang dipicu karena status, komentar miring dan opini yang di dalamnya memuat cara pandang satu personal terhadap yang lain. Alih-alih hendak menunjukkan simpatisan dan membangun interaksi sosial, tak jarang yang terjadi justru malah bullying, diskriminatif dan penghakiman.
Bahkan website resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pada Februari 2020, kasus diamputasi jari salah seorang siswa hingga ditendang sampai meninggal dunia menjadi gambaran ekstrem dan fatalnya intimidasi bullying yang dilakukan oleh pelajar.
Keekstreman dan kefatalan tersebut marak terjadi tidak lain disebabkan oleh cara pandang dan kebiasaan yang keliru menempatkan kekerasan sebagai solusi atas pemecahan suatu persoalan.
Data statistik KPAI menunjukkan pengaduan kekerasan terhadap anak dianalogikan sebagai gunungan es yang tidak pernah mencair, di mana dalam kurun waktu sembilan tahun (2011-2019) mencapai angka 37.381 kasus. Adapun kasus bullying yang terjadi di pendidikan ataupun di sosial media angkanya menyentuh 2.473 laporan dan itupun trennya terus meningkat (sumber: kpai.co.id).
Selain itu keadaan tersebut diperparah dengan kriminalitas yang terjadi dalam lima bulan terakhir di tahun ini. Tindakan pencurian gadget yang dilakukan oleh orangtua marak terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Tatkala polisi menyelidiki, alasannya sangat mengerikan, ” mereka terpaksa mencuri” guna kelangsungan belajar anak-anaknya di rumah.
Misalnya kasus seorang ayah di Garut Jawa Barat yang nekat mencuri smartphone sang majikan demi pembelajaran online putri kesayangannya. Hal itu ia lakukan tidak lain karena tidak memiliki smartphone, sehingga salah satu dari ketiga anaknya yang duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah itu tidak bisa mengikuti belajar via daring dengan teman-temannya (sumber: detik.com).
Pertanyaannya, orangtua mana yang tega melihat anaknya merasa minder terhadap teman-temannya? Apakah ada orangtua yang rela anak-anaknya dikucilkan oleh lingkungan pendidikannya?
Dalam konteks ini tentu kita tak perlu meragukan dan banyak mempertanyakan sejauh mana usaha orangtua untuk menyukupi kebutuhan belajar anak-anaknya. Bukankah orangtua sangat begitu sensitif tatkala mempersoalkan buah hatinya?
Terlebih lagi tatkala orangtua mengetahui bahwa anak kesayangannya tidak bisa mengikuti pembelajaran virtual, sudah barang tentu segala daya upaya akan ia maksimalkan. Banting tulang. Tidak segan dan tidak dipermasalahkan jikalau itu mengharuskannya menjungkirbalikkan fungsi; kaki di kepala, kepala di kaki.
Sengkarut yang kian carut-marut tersebut, sesungguhnya tidak lepas kehadiran sindrom FOMO sebagai tanda ketergantungan manusia atas pencitraan yang dibangun di jagat maya.
Sementara sebagai salah satu dampak positifnya, secara tidak langsung wabah pandemi Covid-19 ini menggenjot kesadaran masyarakat atas pentingnya melek terhadap kemutakhiran teknologi.
Kepemilikan gadget secara merata, pada kenyataannya akan berdampak pada konsep lapisan stratifikasi dan deferensiasi sosial yang telah lama disarkalkan oleh segelintir masyarakat kini mulai mengalami pendefinisian kembali sehingga sifatnya lebih terbuka dan saling melengkapi.
Koneksi Internet sebagai Kebutuhan Pokok
Kepemilikan dan kapabilitas atas gadget pada kenyataannya tidak dapat termaksimalkan fungsi dan manfaatnya untuk menunjang proses pembelajaran selama tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Koneksi gadget dengan internet dalam konteks kelangsungan pembelajaran jarak jauh di sini dapat dianalogikan layaknya ruh dan jasad yang saling melengkapi sekaligus menghidupi.
Dua komponen integral yang tak dapat dipisahkan antara satu sama lain tatkala membicarakan banyak tentang multifungsi kemutakhiran teknologi terhadap peradaban umat manusia.
Bagaimanapun proses pembelajaran di masa pandemi ini sangat bergantung pada penggunaan aplikasi ruang belajar berbasis sosial media yang mengharuskan adanya koneksi internet. Entah itu koneksi internet melalui kouta data kartu perdana atau WiFi Indihome sekalipun.
Atas dasar ketergantungan itu pula pada akhirnya koneksi internet pun menjadi kebutuhan pokok baru yang lambat-laun bersaing ketat dengan upaya pemenuhan kebutuhan primer dalam menjalani kehidupan. Sementara segenap kebutuhan sekunder dan tersier lainnya semakin jauh terpinggirkan.
Ironisnya, bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu secara finansial justru ketergantungan proses pembelajaran dengan koneksi internet tersebut adalah pertaruhan antara mengisi perut untuk bertahan hidup dan mati.
Pendek kata, ketergantungan atas internet itu menambah beban yang mengharuskannya banting tulang ke sana-kemari mencari tambahan pekerjaan sampingan.
Kalau tidak demikian, dengan sangat terpaksa mencari pinjaman uang guna membeli kuota data untuk mengikuti proses pembelajaran. Belum lagi ditambah dengan persoalan tersendatnya sinyal dan lokasi strategis untuk mendapatkan sinyal yang stabil.
Kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim, yang memperbolehkan pengalokasian uang yang diambil dari kartu Indonesia pintar (KIP) untuk membeli paket data nampaknya sedikit membawa angin segar bagi para siswa yang mempunyai KIP.
Sedangkan bagi sebagian siswa yang berstatus miskin sungguhan namun tidak mendapatkan KIP mungkin hanya bisa gigit jari, dan siswa yang kebetulan keturunan borjuis mengabaikan apa pun yang terjadi sama sekali.
Tekanan Psikis sebagai Kawan Terbaik Sepermainan Anak
Selain mengondisikan kembali peran orangtua dan ketergantungan atas internet, pembelajaran jarak jauh juga akhir-akhir ini dipandang berakibat fatal atas keadaan psikis anak didik.
Hal yang demikian diceritakan betul oleh beberapa teman yang berprofesi sebagai guru honorer atau pun tetap di dua-tiga sekolah. Mereka menegaskan bahwa banyak anak didiknya yang merasa rindu dengan rutinitas pembelajaran di sekolah.
Selain itu, ditemukan pula tidak sedikit di antara anak didik yang mengeluhkan capeknya proses pembelajaran dari rumah. Bagaimanapun proses pembelajaran yang sekadar mengerjakan bejibun tugas tanpa penjelasan yang gamblang membuat anak didik mudah bosan dan jenuh.
Lebih lanjut, keluh-kesah tersebut bermula dari cara membimbing dan tuntutan yang dikehendaki oleh orangtua terkadang lebih kerap tampil dengan luapan emosional yang merundung mental anak didik.
Celah borok atas pengalihan proses pembelajaran dari ruang publik ke ruang domestik yang menyebabkan adanya pemangkasan terhadap kebiasaan dalam mengekspresikan perasaan selama belajar sang anak.
Jika sebelumnya para siswa seleluasa mungkin mengekspresikan diri dan perasaannya dalam kebersamaan belajar dengan teman-teman di sekolah maka di masa pandemi ini justru mereka merasa terawasi dan terkungkung karena selama proses belajar dilakukan dengan penuh ketegangan.
Mengapa demikian? Bagaimanapun siswa yang belajar didampingi oleh orangtuanya lebih terkesan ‘menegangkan’, sungkan dan berada di bawah tekanan. Terlebih lagi jika kemampuan sang anak tidak mampu memenuhi ekspektasi orangtuanya yang perfeksionis.
Sebagai dampaknya, alhasil segala bentuk tuntutan, pendiktean dan sikap sentimenal yang ditampilkan oleh orangtua tidak segan lagi meliputi diri sang anak. Terkadang, kalimat-kalimat sarkas, bentakan keras dan peringatan yang dilontarkan orangtua kerapkali membuat down mental sang anak.
Dalam konteks ini, jika kita meminjam cara pandang Robert Frost, bukankah tujuan utama dari pendidikan adalah kemampuan mendengar setiap hal tanpa harus kehilangan tabiat dan kepercayaan diri seseorang yang disebut pembelajar?
Ah, sampai di sini nampaknya benar pula apa yang telah berpuluh-puluh tahun lalu ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara; secara general, pengajaran sesungguhnya untuk “memerdekakan manusia atas hidupnya secara lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan”, (Ahmad Syafii Maarif: 2013).
Penyampaian nasehat, cara membimbing dan sederet harapan yang disampaikan orangtua dengan mengabaikan bagaimana keadaan psikis (batin) sang anak inilah hal yang kurang sehat dalam proses pembelajaran. Sehingga membuat anak didik tidak merasa merdeka tatkala melangsungkan pembelajaran jarak jauh.
Sederet keadaan itulah yang membuat anak didik merasa kurang nyaman belajar di bawah pengawasan orangtua. Mungkin saja, tatkala mereka berada di depan orangtuanya berusaha tampak bersungguh-sungguh dan disiplin.
Sementara di lain waktu mereka sibuk mencari kesempatan untuk berusaha melampiaskan kekesalan, kejenuhan dan ketertekanan psikisnya dengan melakukan hal-hal baru yang sama sekali belum pernah dilakukan sebelumnya.
Tidak menutup kemungkinan, pada upaya pelampiasan tingkat tinggi anak didik melakukan hal-hal negatif, seperti yang pernah terjadi di awal pemberlakuan kebijakan PSBB dan WFH, di mana kasus balapan liar sepeda motor dan tawuran antar pelajar mencuat di banyak tempat. Bahkan, parahnya lagi tidak sedikit pula siswa yang meregang nyawa.
Dari sekian banyak problematika yang nampak ke permukaan, kunci utamanya terletak pada bagaimana kita menyikapi implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan.
Upaya penerimaan, cara pandang dan kebijaksanaan masing-masing pribadi orangtua berperan sebagai eksekutor terakhir yang berdiri di antara manzilatain (dua persimpangan). Baik-buruk dalam konteks membimbing sang anak menjadi jelmaan ekspresif atas dasar sejauh mana pemahaman, wawasan dan pengalamannya.
Sebagai penutup izinkan saya mengutip pernyataan Martin Heidegger; “Belajar berarti membuat segala sesuatu yang kita jawab menjadi hakikat-hakikat yang selalu menunjukkan dirinya sendiri kepada kita setiap saat. Mengajar lebih sulit daripada belajar karena apa yang dituntut dari mengajar: membiarkan belajar”.
Editor: Roni Ramlan
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Catatan: Tulisan ini murni opini penulis, redaksi tidak bertanggung jawab terhadap konten dan gagasan. Saran dan kritik silakan hubungi [email protected]
Jangan lupa berikan reaksi dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya! Selain apresiasi kepada penulis, komentar dan reaksi Anda juga menjadi semangat bagi Tim Redaksi 🙂
Silakan bagi (share) ke media sosial Anda, jika Anda setuju artikel ini bermanfaat!
Jika Anda ingin menerbitkan tulisan di Artikula.id, silakan kirim naskah Anda dengan bergabung menjadi anggota di Artikula.id. Baca panduannya di sini!
Untuk mendapatkan info dan artikel terbaru setiap hari Anda bisa juga mengikuti Fanpage Facebook Artikula.id di sini!

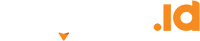




One Comment