Al-Qur’an hadir dalam tataran kehidupan masyarakat manusia dalam wujud yang tak kasat mata. Nabi Muhammad menerima dari malaikat Jibril dalam bentuknya yang kita kenal berwujud oral atau lisan. Begitupun yang terjadi pada masa awal Islam (Ahmad Rafiq, 2012: 71). Tidak bergantung pada teks tertulis seperti kita temukan hari ini, melainkan melalui wujud satuan kata dalam lisan.
Kondisi ini dapat ditemukan, sesudah penyusunan Al-Qur’an—kodifikasi mushaf atau teks—hingga menjadikannya sebagai teks sakral dengan posisi tertinggi dalam ajaran Islam. Karena itu, konfirmasi lisan maupun tulisan dari Al-Qur’an akan selalu menjadi riwayat yang saling berkaitan dari masa ke masa.
| Baca Juga: Penafsiran Al-Qur’an Setelah Rasulullah Wafat |
Sebagai kitab suci, ia telah hidup membersamai kehidupan umat Islam, bahkan masyarakat manusia secara umum. Terlihat dari hasil riset Anne K. Rasmussen mengenai tradisi khataman Al-Qur’an di Pondok Pesantren Darul Falah Jawa Barat, hingga tradisi lainnya yang berwujud kompetisi seperti musābaqah fahmil-qur’ān maupun hifdzil-qur’ān yang dipandang sebagai perlombaan bergengsi dalam kancah pembelajaran Al-Qur’an di Indonesia maupun dunia (Rasmussen, 2010: 74).
Keberadaan tradisi ini menarik perhatian salah satu produser film Amerika, Greg Barker, untuk mengangkatnya dalam suatu kisah. Film garapan Barker tersebut bertajuk “Koran by Heart”, rilis pada tahun 2011, secara umum menyampaikan gambaran betapa bernilainya ajang kompetisi Al-Qur’an internasional di Mesir setiap bulan Ramadan dari tahun ke tahun.
Film besutan Barker tersebut mengisahkan bagaimana nilai kitab suci hidup dalam tradisi negara dan kelas sosial yang berbeda. Kondisi ini berawal dari masuknya Al-Qur’an dalam lini kehidupan manusia sebagai wahyu Tuhan lalu disampaikan oleh Nabi, hingga pada akhirnya masyarakat sebagai penerima, meresapi—menerima, merespon, dan bereaksi—Al-Qur’an untuk ragam tujuan dan kebutuhan.
Kehidupan berbeda terbentuk dari paradigma plural dalam membaca Al-Qur’an. Social setting yang ditampilkan lebih banyak menampilkan sisi khas Timur Tengah yang ditunjukkan melalui pemilihan tokoh utama. Walaupun, dalam beberapa adegan menyuguhkan bagaimana Al-Qur’an juga ikut hidup dan mengambil peran dalam pemikiran masyarakat Australia dan Italia sebagai contohnya.
Ia mengemas alur kisah dalam sajian yang ciamik. Barker mendeskripsikan bagaimana potret pembacaan muslim atas Al-Qur’an bervariasi dan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan masyarakat dan keluarga. Menceritakan tiga orang anak berusia 10 tahun dari kota Tajikistan, Maladewa dan Senegal yang memiliki tujuan dan pemikiran yang sama; pergi ke Mesir untuk mengikuti kompetisi.
Tokoh pertama, Nabiollah berasal dari Tajikistan, dibesarkan dalam lingkungan yang peduli akan pendidikan agama (terutama dalam menghafal Al-Qur’an). Sampai pada potret adanya kekhawatiran si ayah terhadap pencapaiannya dalam penguasaan ilmu sekuler dasar, salah satunya aksara Tajik.
Lain halnya dengan Rifdha, hidup dalam keluarga yang cenderung fundamentalis dan patriarki. Dengan kata lain, ayah sebagai kepala keluarga memiliki andil besar dalam mengarahkan masa depan Rifdha sebagai anak perempuan.
Sedangkan Djamil mewakili figur anak laki-laki muslim dari kota Senegal, Afrika Barat, tumbuh dalam doktrin citra Al-Qur’an dan agama yang membawa kedamaian. Dituntut untuk menghafal dan menerapkannya dalam ritme karakter kehidupan—meminjam Anne K. Rasmussen—agar dapat meredakan peperangan juga kekerasan di dunia manusia, sebagai implikasi logis dari Al-Qur’an sebagai petunjuk.
Berasal dari latar lingkungan agamis dan kelas sosial menengah ke bawah, struktur pendidikan orang tua Djamil memotivasi anak-anaknya untuk menghafal Al-Qur’an dengan tujuan bisa pergi ke Mesir. Sejalan dengan pandangan masyarakat sekitar, Mesir sebagai pusat keilmuan dan kesuksesan bagi orang-orang muslim.
Kisah lain yang ditampilkan oleh Barker adalah sosok Abdullah dari Mesir. Sebagaimana dikatakan oleh ibunya, ia menghafal al-Qur’an sebagai sarana menjadi anak saleh dan bermanfaat. Alasan ini banyak ditemukan pula di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar. Dalam konteks yang jauh, hidup juga paham Islam yang beragam, masuk serta mengakar dalam pemikiran masyarakat.
| Baca juga: Al-Qur’an Hidup di Masyarakat |
Seperti banyaknya didirikan lembaga-lembaga untuk menghafal Al-Qur’an sebagai sarana pendidikan formal atau non-formal. Fenomena ini, pembacaan (penerimaan) muslim terhadapnya oleh Rafiq disebut sebagai bentuk dari keyakinan akan kesucian Al-Qur’an (Ahmad Rafiq, 2012: 75). Terlepas dari apakah mereka paham bahasa Al-Qur’an atau tidak, sebagaimana terjadi kepada Rifdha dan Nabiollah. [SJ]
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Catatan: Tulisan ini murni opini penulis, redaksi tidak bertanggung jawab terhadap konten dan gagasan. Saran dan kritik silakan hubungi [email protected]
Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang artikel ini? Jangan lupa berikan reaksi dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya!
Anda juga bisa mengirimkan naskah Anda tentang topik ini dengan bergabung menjadi anggota di Artikula.id. Baca panduannyadi sini!
Untuk mendapatkan info dan artikel terbaru setiap hari Anda bisa juga mengikuti Fanpage Facebook Artikula.iddi sini!

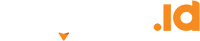




0 Comments