Al-Qur’an adalah kitab suci yang menjadi pegangan hidup bagi umat Islam di seluruh dunia, baik dalam hal-hal yang terkait relasi dengan Allah maupun yang terkait relasi dengan manusia.
Umat Islam yakin bahwa kitab ini berlaku sepanjang zaman sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad saw 14 abad yang lalu. Sebagai mukjizat terbesar dan pedoman hidup, Al-Qur’an harus dimengerti maknanya dan setelah itu bisa diaplikasikan isinya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan fungsi dan keistimewaannya.
Karena Al-Qur’an diturunkan dengan bahasa yang tidak begitu mudah dipahami maka kemudian sebagai makhluk yang berpikir, manusia berusaha memahami isi kandungannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan mendayagunakan potensi akal, melalui upaya memahami dan menafsirkannya.
Studi terhadap Al-Qur’an dan metodologi tafsir sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan, produk-produk tafsir dari satu generasi kepada generasi berikutnya memiliki corak dan karakteristik yang berbeda seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia, sejak turunnya Al-Qur’an hingga sekarang.
Di awal sejarahnya penafsiran Al-Qur’an dimulai dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan hadis nabi, atau pendapat sahabat nabi dan tabiin. Masa ini disebut juga dengan periode klasik yang berawal pada akhir masa tabiin sampai akhir dinasti bani Abbasyiah pada tahun 650 H/1258 M.
Di antara ulama klasik yang dianggap sebagai penulis tafsir pertama adalah Sufyan bin Uyaynah, Waki‟ bin Djarrah, Syu‟bah bin Hajjaj, Yazid bin Harun dan Ibnu Humaid.
Kemudian mereka diikuti oleh al-Thabari yang menulis kitab tafsir Jami‟ al-Bayan fi Ta‟wil Ayi al-Qur‟an. Di antara mufasir klasik yang lain adalah Abu Ishak al-Zujjaj (w. 310 H) yang menulis tafsir Ma‟anil Qur‟an. Abu Bakar Ahmad al-Djashash (w. 370 H) yang menulis tafsir Ahkam al-Qur‟an. Abu Ali al-Farisi (w. 377 H). Abu Bakar An-Naqas (w. 324 H). dan Abu Ja‟far An-Nahhas (w. 351 H).
Pada masa ini mufasir secara keseluruhan tidak mempertimbangkan perubahan kebutuhan umat Islam, dalam tafsir mereka banyak tradisi tafsir yang menggunakan pendekatan literal dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an.
Penafsiran Al-Qur’an yang cenderung tekstualis adalah penafsiran yang memperhatikan aspek kebahasaan semata. Konteks historis yang ada ketika Al-Qur’an diturunkan tidak menjadi pertimbangan yang berarti dalam proses penafsiran Al-Qur’an, akhirnya pemahaman yang muncul cenderung tekstualis dan literalis.
Penulis memandang sebab para mufasir awal tidak memperhatikan konteks sosial budaya dalam menafsirkan Al Quran, karena al Quran di masa awal turunnya telah sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial budaya di masanya.
Meskipun setelah 4 abad era tabi’in berjalan perkembangan sosial budaya pada masa dinasti Abbasiyah tidak berubah secara signifikan, sehungga pendekatan tekstual masih digunakan dan masih relevan di zamannya. Hal ini yang menjadikan para mufassir awal cenderung pada pendekatan tekstual dalam menafsirkan Al-Qur’an.
Contoh yang paling jelas dari penafsiran tektualis dapat ditemukan saat ini di kalangan orang-orang yang disebut sebagai kelompok tradisionalis atau salafi. Menurut mereka Al-Qur’anlah yang harus menuntun umat Islam, bukan apa yang disebut kebutuhan-kebutuhan modern. Mereka menganggap makna Al-Qur’an sebagai sesuatu yang sudah tetap dan universal dalam aplikasinya.
Misalnya, jika Al-Qur’an mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi empat orang istri, maka ini harus berlaku selamanya, tanpa perlu memperhatikan konteks sosio historis ketika teks ini diwahyukan. Bagi mereka, alasan Al-Qur’an membolehkan seorang laki-laki menikahi empat istri pada abad ke 1 sampai 7 di Hijaz tidaklah penting.
Dari contoh tersebut dapat di asumsikan bahwa Al-Qur’an Shalih likulli zaman wa makan dalam paradigma tafsir klasik dipahami dengan cara memaksakan konteks apapun ke dalam teks Al-Qur’an.
Di masa modern sekarang metode penafsiran seperti ini menurut hemat penulls cenderung agak sedikit dipaksakan, sebab dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi sosial budaya yang telah berubah menjadikan penafsiran tekstual yang lama agak sedikit tidak relevan dengan kondisi sekarang.
Maka usaha yang perlu dilakukan untuk merenovasi penafsiran yang sifatnya tekstualis tersebut, ayat-ayat dalam Al-Qur’an hendaknya ditafsirkan sesuai dengan semangat zamannya.
Penafsiran seperti inilah yang disebut dengan penafsiran kontekstualis, yakni penafsiran yang menekankan konteks sosio historis dalam memahami ayat Al-Qur’an.
Para mufasir yang mendukung metode penafsiran semacam ini ketika menafsirkan Al-Qur’an adalah dengan memahami konteks politis, sosial, historis, kultural dan ekonomis ketika ayat-ayat ini diwahyukan, diinterpretasikan, dan diaplikasikan.
Jadi, mereka mengusulkan tingkat kebebasan yang lebih tinggi bagi ilmuwan muslim modern untuk menentukan apa yang bisa dan tidak bisa berubah. Sebagai contoh adalah ayat-ayat yang berbicara tentang pluralisme, perbudakan, warisan, politik, gender, deskriminasi dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan.
Dengan asumsi tersebut maka Al-Qur’an perlu ditafsirkan secara terus menerus sehingga tidak kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman. Ini juga berarti bahwa meskipun selama ini sudah banyak tafsir yang ditulis oleh para mufasir, tidaklah perlu ada sakralisasi terhadap hasil penafsiran.
Sebab, sakralisasi penafsiran Al-Qur’an tidak saja dapat disebut sebagai syirik intelektual, tetapi juga dapat menyebabkan dinamika pemikiran umat Islam mengalami stagnasi.
metode penafsiran dengan corak kontekstual akan menghindarkan mufasir dan hasil penafsirannya dari sifat truth claim (klaim kebenaran). Seorang mufasir juga harus bebas dari tendensius-tendensius atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya politik maupun kepentingan pribadi agar penafsirannya objektif sesuai dengan konteks keilmuan.
Hasil penafsirannya hendaknya menjadi jawaban atas segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat, bukan memicu adanya konflik karena kepentingan pribadi maupun politik di dalamnya, seperti yang pernah terjadi pada masa konflik antara Ali dan Muawiyah.
Pada masa itu penafsiran agak berbau politik karena situasi politik yang memanas antara Ali dan Muawiyah. Dari peristiwa tersebut dapat diambil sebuah pembelajaran, bahwa para mufasir harus bebas dari tendensius-tendensius yang menyebabkan hasil penafsirannya menjadi tidak objektif.
Namun demikian, apabila definisi di atas tidak dipahami dengan cermat, maka akan menyesatkan banyak orang, sebab akan terkesan bahwa Al-Qur’an harus mengikuti perkembangan zaman.
Sebuah statemen yang tidak boleh diucapkan oleh siapapun. Secara terperinci maksud dari tafsir modern kontemporer adalah merekonstruksi kembali produk-produk tafsir klasik yang sudah tidak memiliki relevansi dengan situasi modern.
Tafsir seperti inilah dalam kacamata studi agama yang diperlukan dalam konteks kekinian maupun di masa depan, tafsir yang sifatnya inklusif bukan ekslusif yakni menafsirkan Al-Qur’an tidak hanya mengandalkan perangkat keilmuan seperti yang digunakan para penafsir dulu, yang hanya terkungkung dalam perspektif ilmu agama seperti ilmu nahwu,sharaf, ushul fiqh dan balaghah, tetapi juga menggunakan ilmu-ilmu modern yang berkembang dewasa ini seperti teori sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, sejarah, gender dan sebagainya.
Dari berbagai pendekatan yang digunakan maka output dari produk-produk penafsiran adalah untuk menjawab segala permasalahan umat, serta membawa perdamaian bukan menimbulkan konflik. Meskipun demikian penafsiran dengan corak kontekstualis tidak harus mengabaikan tradisi Islam klasik sepenuhnya.
Sebaliknya kita harus mengambil keuntungan dari tradisi-tradisi penafsiran sebelumnya. Artinya penafsiran dengan corak tekstual dan kontekstual tidak selamanya berseberangan kedua corak penafsiran tersebut bisa di integrasi di interkoneksikan antara Normativ-teologis (tekstual) dan sosio-historis (kontekstual).
Akhirnya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa penafsiran Al-Qur’an adalah sebuah proses yang tak pernah mengenal titik henti. Ia telaah dimulai sejak zaman nabi dan terus berlangsung hingga masa sekarang.
Kebenaran tafsir pun tak pernah mengenal kata mutlak sehingga wajar jika ia terus diperbincangkan dan tidak jarang juga mendapat kritikan tajam, terutama ketika produk-produk penafsiran tersebut mangandung bias ideologis dan terkesan tak lagi relevan dengan perkembangan zaman.
Oleh karena itu dibutuhkan perubahan metodologi dalam penafsiran Al-Qur’an, sehingga pembacaan Al-Qur’an akan bersifat produktif dan prospektif. Dengan cara demikian, maka produk-produk penafsiran yang dihasilkan pun akan senantiasa kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.
Tafsir seperti inilah yang ingin diperkenalkan lewat kacamata Studi Agama dan Resolusi Konflik, agar dapat menjawab persoalan-persoalan umat dewasa ini yakni tafsir yang sifatnya inklusif dan kontekstual.

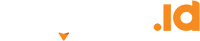




0 Comments