“Saya tidak setuju pendapatmu, tapi akan saya bela mati-matian hakmu untuk berpendapat.”—Voltaire.
Kutipan kalimat dari Voltaire, filsuf cum sastrawan asal Prancis, memiliki makna yang sangat mendalam. Sebuah napas segar bagi kebebasan berpendapat dan sebuah hasil refleksi yang keluar dari kepala dingin. Ya, semua orang pada dasarnya bebas berpendapat. Bebas mengafirmasi atau menegasi pendapat seseorang.
Belum lama ini laman media sosial di Indonesia gaduh oleh ulah pegiat media sosial sekaligus yang kerap dikenal sebagai buzzer, Eko Kuntadhi, yang menghina Ning Imaz di Twitter. Kegaduhan tersebut bermula dari cuitan Eko Kuntadhi yang mengunggah potongan video Ustadzah Imaz Fatimatuz Zahra atau yang kerap disapa Ning Imaz dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri (Triono, 2022).
Sebelumnya, Ning Imaz menjelaskan tentang tafsir QS. Ali Imran ayat 14 dalam video yang diproduksi oleh NU Online. Video tersebut juga terdapat pada TikTok NU Online dengan judul Lelaki di Surga Dapat Bidadari, Wanita Dapat Apa?
Dari potongan video tersebut, Eko Kuntadhi mengunggah cuitan dengan keterangan yang bertendensi menghina. Kasar. Cuitan Eko tersebut memancing beberapa pengguna Twitter untuk melakukan hal serupa. Tak pelak, karena ulah Eko tadi, netizen banyak yang geram, sebab yang dihina Eko tersebut merupakan salah seorang pengasuh pondok dan keilmuannya juga sudah mumpuni.
Berawal dari ulah digital, Eko pun kena tulah di dunia korporeal. Ia harus mempertanggungjawabkan cuitannya yang dilakukan dengan klik tersebut dengan datang langsung menemui Ning Imaz di Lirboyo, Kediri.
Melihat fenomena tersebut, satu hal yang perlu digarisbawahi: dunia digital sangat mempengaruhi dunia korporeal. Dunia tersebut, baik digital maupun korporeal, keduanya saling berjalin kelindan. Tak dapat dipisahkan. Oleh karenanya mengenali ruang digital dan cakap di dalamnya menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Selayang Pandang Dunia Digital
Kita hidup di dunia yang tak lagi berwajah tunggal. Jika dulu dunia adalah kenyataan secara korporeal, hari ini—terutama setelah merebaknya Pandemi Covid-19—dunia menampakkan wajah barunya. Nahasnya, dunia yang menampakkan wajah baru tersebut menjadikan kita sebagai manusia terjerembab dalam kegagapan yang mengenaskan. Dunia digital adalah dunia baru yang masih asing bagi sebagian orang, bahkan dianggap berbeda sama sekali dengan dunia korporeal saat ini. Nyatanya tidak seperti itu.
Sekilas dunia digital ini nampak mengerikan dan dapat menyebabkan seseorang tenggelam secara tragis—seperti kasus Eko Kuntadhi. Memang, dunia digital ini pada dasarnya belum lama bertumbuh kembang, khususnya di Indonesia.
Dunia digital ini adalah anak kandung dari revolusi digital. Minghadi Suryajaya (2018) mengatakan bahwa tahun 2016 merupakan tahun revolusi digital bagi Indonesia. hal itu dapat dilihat dari pergeseran status quo pada berbagai sektor industri. Selain itu, dunia digital semakin menjadi-jadi setelah semua kegiatan “dialih-wahanakan” dalam gawai dan komputer karena Covid-19. Satu-satunya alternatif untuk meghadapi kehadiran digital ini yaitu bersikap adaptif. Jika tidak, ketertinggalan dan keterasingan akan dengan lekas menggilas sendi kehidupan kita.
Saya jadi teringat alegori goa Plato yang pada intinya mengatakan bahwa jiwa manusia sesungguhnya terpenjara dalam tubuh, raga, yang sifatnya fana. Jika dikorelasikan dengan keadaan saat ini, sesungguhnya manusia tubuhnya terpenjara di rumah, namun jejaring dan pikiran-pikirannya bisa mengembara ke mana-mana hanya dengan klik di dunia digital.
Seperti halnya fenomena Eko Kuntadhi yang telah dijelaskan di atas, penggunaan klik dalam gawai bisa menggemparkan jagat media sosial. Meski tubuhnya di rumah, kamar, atau entah di mana, tapi karena cuitannya, ia harus menanggung banyak cibiran dan harus meminta maaf secara vis a vis dengan pihak yang bersangkutan.
Belajar dari fenomena Eko Kuntadhi yang dengan asal klik hingga ia kena getahnya, satu poin besar yang kiranya perlu kita ulas setapak demi setapak. Berjejaring, berpendapat, dalam dunia digital, bermedia sosial, kiranya tak hanya membutuhkan effort untuk sekadar klik dengan jari. Namun saat ini keadaan menganjurkan kita untuk cakap dan bijak dalam menggunakannya. Agar dapat berlaku cakap, bijak, dan santun, tentunya diperlukan etika yang baik pula. Hal itulah yang akan diurai lebih lanjut selanjutnya.
Menjadi Bijak dalam Menapaki Dunia Digital
Menjadi seseorang yang bijak tak bisa berangkat dari ruang hampa. Perlu banyak pengalaman dan tentunya tingkat literasi yang mumpuni. Sama halnya dalam dunia digital. Agar menjadi seorang yang bijak, diperlukan integritas dalam literasi digital.
Literasi digital sendiri merupakan pengetahuan serta kecakapan manusia sebagai pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain-lain. Kecakapan manusia dalam memanfaatkan media digital ini tak terlepas dari kemampuannya dalam mengerjakan, mengevaluasi, menemukan, dan memanfaatkan media digital secara bijak sesuai dengan kegunaannya (Suherdi, 2021).
Dalam literasi digital, setidaknya ada delapan elemen esensial yang berperan untuk mengembangkan literasi digital itu sendiri (Belshaw, 2011), yaitu:
- Kultural, yaitu pemahaman mengenai ragam konteks pengguna digital;
- Kognitif, yaitu daya pikir dalam menyikapi sebuah konten;
- Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual;
- Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring serta komunikasi di dunia digital;
- Kepercayaan diri yang bertanggung jawab;
- Kreatif, yaitu melakukan hal baru dengan cara-cara baru;
- Kritis dalam menyikapi konten dan semua informasi yang ada di dunia digital.
Tak cukup itu, untuk menjadi bijak dalam dunia digital, seseorang tersebut juga membutuhkan beberapa prinsip, seperti pendapat Kristen J. Worden yang dikutip oleh F. Budi Hardiman dalam bukunya Aku Klik, Maka Aku Ada (2021). Worden menafsirkan etika keutamaan Aristoteles lalu mengemasnya dalam empat prinsip media sosial guna membangun persahabatan antar-pengguna media sosial.
Pertama, Worden menganjurkan agar kita bersikap inklusif dan terbuka terhadap berbagai perspektif tanpa mengucilkan yang berbeda. Kedua, kita mengendalikan diri dan menahan diri agar tidak dengan mudah merundung seseorang di ranah digital (media sosial), menahan diri untuk tidak menulis ujaran kebencian, karena kita sadar, bahwa manusia merupakan makhluk yang rentan di hadapan kata-kata.
Ketiga, melakukan diskresi—kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi (KBBI). Menyadari bahwa dalam komunikasi digital tak perlu ada ekspektasi untuk jawaban segera, maka kita memiliki jeda waktu untuk memilih-pilah teks. Keempat, peka terhadap pemirsa. Kepekaan terhadap pemirsa ini bertujuan agar mereka yang tidak ikut berkomentar tidak merasa terasing dan tidak tersinggung oleh apa yang kita unggah di media sosial.
Keempat hal yang dikatakan oleh Worden tersebut pada akhirnya membuat manusia berkesadaran penuh dan menjadi lebih bijak. Pasalnya tindakan klik dalam dunia digital tak hanya sekadar klik, lebih jauh lagi, klik yang kerap kali kita lakukan berhubungan dengan kesadaran moral.
Eko Kuntadhi sebenarnya sah-sah saja jika tak sependapat dengan konten yang diunggah oleh Ning Imaz. Toh para ulama juga memiliki banyak ragam perbedaan penafsiran terkait QS. Ali Imran ayat 14 tersebut. Tapi ada yang luput dari Eko Kuntadhi dalam cuitannya. Sangat luput bahkan. Ia gagal memahami adagium yang masyhur, al-adabu fauqa al-ilmi (adab lebih tinggi daripada ilmu). Etika bermedia sosial dan kesadaran dalam ruang digital tak diperhitungkannya. Dari sanalah kita perlu belajar untuk menjadi bijak.
Jika telah mampu berlaku bijak dalam media digital, setidaknya kejadian seperti Eko Kuntadhi di atas tak perlu, dan jangan sampai, terulang. Kiranya sudah jelas, dari fenomena yang terjadi, kita perlu mengambil jarak. Mengambil jeda. Untuk sekadar melihat sesuatu lebih jernih, tidak tergesa-gesa, dan penuh kesadaran. Sebab dua dunia—digital dan korporeal—saat ini dapat berjalan dan saling mempengaruhi hanya lewat satu jari. Oleh karena itu—meminjam adagium Jawa—tetep iling lan waspodo dalam melakukan apapun. Tetap bebas, asal tidak bebal!
Referensi:
Belshaw, D. A. (2011). What is ‘Digital Literacy’? A Pragmatic Investigation. Durham: Durham University.
Hardiman, F. B. (2021). Aku Klik maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
Suherdi, D. (2021). Peran Literasi Digital Di Masa Pandemik. Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna.
Suryajaya, M. (2018). Wonderful Indonesia: Revolusi Tour & Travel Digital. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Triono, A. L. (2022, September 13). Pegiat Medsos Eko Kuntadhi Hina Ning Imaz Lirboyo di Twitter. Retrieved September 20, 2022, from nuonline: https://www.nu.or.id/nasional/pegiat-medsos-eko-kuntadhi-hina-ning-imaz-lirboyo-di-twitter-Op3PD
*Tulisan ini merupakan hasil refleksi diskusi mingguan tim redaksi Artikula.id
Editor: Sukma Wahyuni
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Catatan: Tulisan ini murni opini penulis, redaksi tidak bertanggung jawab terhadap konten dan gagasan. Saran dan kritik silakan hubungi [email protected]
Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang artikel ini? Jangan lupa berikan reaksi dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ya!
Anda juga bisa mengirimkan naskah Anda tentang topik ini dengan bergabung menjadi anggota di Artikula.id. Baca panduannya di sini!
Untuk mendapatkan info dan artikel terbaru setiap hari Anda bisa juga mengikuti Fanpage Facebook Artikula.id di sini!

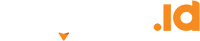


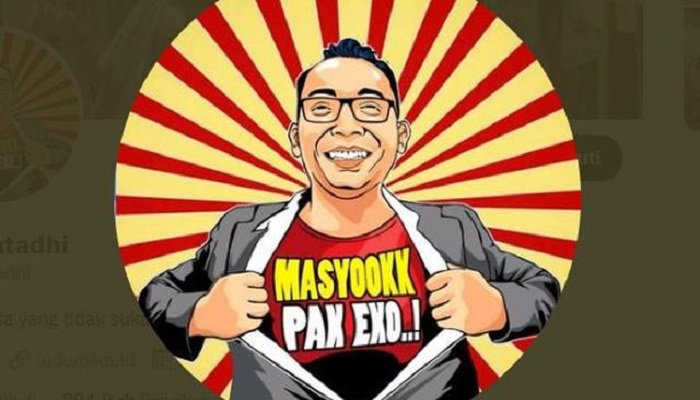

0 Comments